.
.
.
Tubuh berbalut jaket tebal itu membara, suhu yang seharusnya membuat beku malah tak terasa sama sekali. Aspal berlapis es tipis tak menghalangi Irish untuk tetap memacu tungkai. Entah sudah berapa lama ia saling kejar-kejaran dengan laki-laki yang berukuran dua kali lipat dirinya. Kepulan asap dari mulut dan lubang hidung kian menghalangi penglihatan, ia tak tahu sejauh mana sudah berlari.
Ia bersumpah tak melakukan kesalahan hari ini! Atau mengganggu teman sekelasnya karena memasang roman angkuh. Betul-betul pergi membeli cemilan saja ke minimarket tak jauh dari rumah Paman, tempat Irish tinggal.
Sekeliling tampak asing, jalan bercabang ke kiri dan kanan menambah frustrasi otak yang mencari cara untuk menyelamatkan diri. Rumah dan bangunan jelas berbeda, suasana sekitar pun remang-remang berpencahayaan minim, noda coretan di tembok, bak sampah terjungkal, sampai orang terbaring berteman botol kosong, lokasi yang mustahil Paman sudi menetap. jadi sebenarnya Irish ada di mana?
Menggeleng cepat, ia terlalu buru-buru untuk mempertanyakan hal yang sudah jelas, toh, dirinya memang benar tersesat. Daripada makin memperpendek jarak antara ia dengan kemungkinan mati oleh kepalan tangan, atau hujaman benda tipis yang tersembunyi. Irish tak mengacuhkan perih di tumit dan mengambil jalan kiri. Suara geraman dari arah ia datang memaksa gadis tujuh belas tahun itu memompa jantung tanpa istirahat.
Tanpa basa-basi Irish memasuki pekarangan yang lebih tak terurus dari yang lain, rumah dengan vandalisme paling banyak dan pagar yang hilang sebagian. Merangsek ke dalam menggunakan berat tubuh demi mendobrak pintu sekuat tenaga, lalu membantingnya hingga tertutup lantas mendorong lemari setinggi dagu ke depan pintu.
Bunyi benturan keras terdengar, Irish pasrah bersandar pada lemari seraya menahan supaya benda itu tak jatuh menimpanya. Ponsel di tangan tengah sibuk memanggil nomor yang dinamai 'Paman'. Sayang, hanya bunyi beep yang membalas, lelaki kepala empat yang mengasuh Irish sejak balita tak menjawab panggilan keponakan tersayang.
"Buka!"
Teriakan berat diikuti gebrakan keras membuat ponsel Irish terpental ke bawah meja. Berkat kekuatan gorila milik siapa pun orang sinting di balik pintu, lemari nyaris menimpanya, beruntung itu hanya sedikit menggores lengan karena ia berhasil mengelak ke samping. Irish bergegas menaiki anak tangga menuju lantai kedua. Derit lantai makin membuat ngeri, bayang-bayang terperosok gara-gara pijakan rapuh tak terurus menghantui, beberapa bagian sudah ambruk menciptakan lubang dengan kayu mencuat dari pinggirnya.
"Paman ... jemput aku ...." Merengek seraya merayap ke bawah ranjang tua yang dipenuhi tumpukan baju lusuh. Oksigen terasa berhenti di tenggorokan saat-saat mendapati sepasang kaki ikut masuk ke kamar, tak lama setelahnya. Tersadar mendapati lelaki itu membawa pemukul kasti dengan noda kecokelatan memenuhi sebagian sisi.
Peluh bercampur air mata memenuhi wajah putih pucat Irish. Dua lengan ia gunakan menutup mulut dan hidung, mengabaikan fakta aliran merah di punggung tangan yang berasal dari luka di lengan kiri atas, berjuang agar tak mengeluarkan suara, sekadar bernapas pun ia mesti hati-hati.
Kalau tahu bakal diburu orang gila, ia rela tak dapat makan cemilan sehari dua hari, toh, belanjaannya pun entah ke mana sekarang. Ini juga salah Paman karena tak mau pindah dari Detroit, ke mana saja tak masalah asal bukan di kota ini, kota yang mengajarkan bahwa manusia hanya punya satu nyawa. Batinnya dibuat ketar-ketir ketika teringat berita tentang kriminal yang mencuri mata setiap korban-korbannya. Hari sial untuk Irish, jika betul orang yang mengitari seisi kamar mencari-cari ia adalah penjahat buron yang dimaksud. Apa Irish akan jadi mayat tak bermata selanjutnya? Membayangkan itu spontan membangkitkan bulu kuduk.
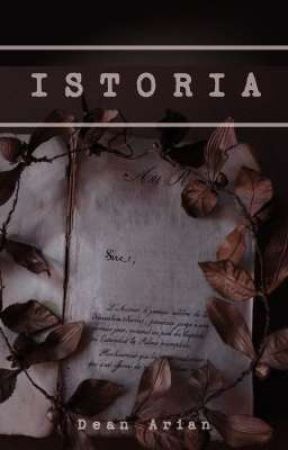
YOU ARE READING
ISTORIA
Short StoryKumpulan Cerpen #17+ (for blood and thriller content) . . . Masih serupa malam sebelum-sebelumnya, kami terbangun bersama dengan peluh yang membasahi baju. Langit masih enggan menyingkap tabirnya yang gulita, bulan malas dan meringkuk di balik seli...

