Kota Promellie merupakan pusat hiburan abad ini. Kebanyakan selebritas papan atas berasal atau pernah menetap di Promellie. Hal itu bukan tanpa alasan sebab Promellie memiliki fasilitas memadai untuk mereka yang benar-benar serius berkecimpung dalam industri tersebut. Salah satunya ialah Akademi Touchme, sebuah sekolah asrama untuk remaja yang menyenangi seni. Mulai dari tarik suara, peran bahkan bagi yang bermimpi menjadi maestro.
Aku lahir dan besar di Promellie. Baik dari keluarga ayah maupun ibuku, semua merupakan alumni atau tengah bersekolah di Akademi Touchme. Ayahku seorang pianis papan atas, sementara ibuku adalah penyanyi opera. Keduanya sudah sering berkeliling dunia untuk mempertunjukkan keahlian mereka. Belasan album pun telah mereka keluarkan dan semuanya menjadi hits di jenisnya. Tak ada pecinta musik klasik yang tak mengenal ibu maupun ayahku.
Bibiku malah anggota grup yang disebut TCM48, sebuah grup yang terdiri dari 48 orang alumni Akademi Touchme jurusan idola, 24 wanita dan 24 pria. Untuk bisa masuk grup tersebut, seorang murid harus berada pada enam besar predikat murid terbaik. Mereka akan berada pada TCM48 setidaknya selama delapan tahun setelah kelulusan dari Akademi Touchme. Bila masa kontrak mereka habis, mereka bebas menentukan arah dan tujuan hidup mereka. Apakah ingin menjadi tenaga pengajar di akademi atau merintis karir mandiri. Kalau bibiku, sih, lebih memilih untuk menjadi instruktur tari kontemporer di sanggar miliknya. Sekali-sekali bibi juga punya pertunjukan bersama teman-temannya.
Dan kini, aku dihadapkan oleh takdir. Di depanku ada tablet yang lampu LED-nya berkedip, tanda e-mail masuk. Isinya sudah kupastikan tentang diterima atau tidaknya aku di Akademi Touchme. Soalnya, berdasarkan jadwal beredar, pada pukul delapan pagi pihak sekolah akan mengirimkan pengumuman. Bibiku sudah mengetuk pintu selama paling tidak lima menit. Suaranya penuh semangat tatkala menanyakan hasil yang kuterima. Tapi, bahkan setelah memandang tabletku selama setengah jam, aku belum juga menyentuhnya. Maksudku, aku sudah tahu kalau aku mendapatkan kelulusan mutlak. Ujianku berjalan dengan amat baik: menyanyi, menari, bermain peran dan alat musik. Tim penilai pun memberikan pujian berarti--walau tentu saja aku masih mendapat kritikan di beberapa titik akibat kurang konsentrasi karena tegang. Lagi pula, aku sudah berlatih hampir seumur hidup. Sungguh suatu pertanyaan besar bila aku sampai tak berhasil. Bukankah ada pepatah yang menyebutkan kalau "usaha keras tidak akan mengkhianati"?
"Auleen! Keluarlah dan biarkan bibi mengetahui berita baik darimu!" Suara bibi menggelegar: lantang dan berkharisma. Wanita itu sudah selesai dari TCM48 sejak tiga belas tahun lalu, tapi aura idolanya belum hilang juga. Aku tidak akan menyangkal bila orang-orang menyebut bibi sebagai bintang yang sesungguhnya. Dia selalu bersinar bahkan di luar panggung sekalipun.
"Auleen? Kaudengar bibi, kan? Ayolah. Cepat katakan hasilnya pada bibi!" Bibi terdengar memohon, tapi aku masih bergeming.
"Auleen?"
"Masuklah, Bi. Tidak dikunci, kok," ucapku akhirnya.
Pintu kamarku terbuka. Kepala bibi menyembul dari luar. Rambut panjang jingganya yang terurai langsung melayang terkena angin yang berasal dari jendela kamarku yang terbuka lebar. Tirai panjangnya mengenai wajah bibi, membuat wanita itu menggerutu kesal. Ketika ia telah melangkah sepenuhnya ke dalam kamarku, aku menyunggingkan senyum simpul. Tangan bibi bergerak gelisah. Dia menggigit bibir sebelum berbicara, "Hei, kau baik-baik saja? Sepertinya kau terlihat tak senang. Apa isi e-mail-nya tidak seperti harapan?"
Aku melirik cermin yang berdiri di ujung kamarku. Tampangku amat payah: tidak ada senyum atau raut antusias di sana. Mata hijauku nampak sayu dan rambut indigo yang selalu diikat rapi kini terlihat kusut. Hal ini memang tidak dipungkiri, aku sudah hampir seminggu tidak tenang saat tidur. Bukan karena tegang menunggu hasil ujian, tapi karena hal lain.
Bibi bergerak mendekat ke arah meja belajarku--kurasa hendak mengecek tablet, sementara aku berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Walau perasaanku gundah, bukan berarti penampilanku harus berkata demikian pula.
Suara bibi terdengar beberapa saat setelah aku selesai dengan wajahku. "Kautahu, Auleen. Hasilmu memang sesuai yang bibi duga, tapi kau akan sanggup bukan? Maksud bibi ..." dia terdengar tak yakin untuk meneruskan kalimat. Kudengar bibi menghela napas panjang, "... kau tak harus melakukan ini, Auleen."
Mataku menyisir area kamar mandiku: bathtub yang kering, tirai yang tak terpasang dengan benar, handuk dan peralatan mandi yang berserakan di lantai. Ruangan ini seperti telah diterjang tornado dan dibiarkan terbengkalai. Punggungku turun menyusuri tembok, duduk memeluk lutut dengan pandangan lurus ke depan. Posisi ini membiarkan aku dapat menciumi bau badanku yang ternyata tak sedap. Aku tak pernah menyangka seminggu tak mandi membuat aku bisa sebau ini.
Langkah samar terdengar mendekat menuju kamar mandi. Kala pintu terbuka, wajah khawatir bibilah yang pertama kali kutangkap. Dia berjongkok di sebelahku, memandangiku hati-hati sambil memainkan ujung rambutnya. "Auleen ... Apa kau baik-baik saja? Ini sudah seminggu."
Aku mengangguk pelan. Saking pelannya, aku bahkan tak yakin kalau bibi benar-benar melihatku menjawab pertanyaannya. Akhirnya aku berkata, "Aku baik-baik saja, Bi. Tak apa-apa."
"Kepergianmu ke akademi bisa ditunda, kok. Aku bisa meminta kepala sekolah--"
"Aku bersekolah di sekolah biasa saja," selaku, yang membuat bibi nampak amat terkejut. Dia terlihat ingin mengutarakan sesuatu lagi, tapi segera kupotong, "Sudahlah, Bi. Aku tak butuh nasihat lagi." Aku berdiri dan meninggalkan kamar mandi dengan langkah gontai.
Memasuki kamar yang tidak kalah terbongkarnya seperti kamar mandiku, bibi kembali memanggilku. Di sela-sela ucapannya, aku mendengar isakan. Bibi gusar. Bibi marah padaku. Aku yakin itu. "Orang tuamu tidak menginginkan ini, Auleen," ujarnya dengan nada gemetar.
Wajahku memanas. Rasanya ingin menangis setiap orang tuaku diungkit, menandakan bahwa aku sangat cengeng. Mereka pasti tak akan senang bila melihatku seperti ini. Itu pun bila mereka memang ada di sini.
Andai orang tuaku masih ada di sini.
"Katakan padaku, Bi," ucapku lantang, "apakah seorang anak berumur dua belas tahun mampu berjalan di atas mimpinya lagi ketika orang tuanya meninggalkan dia karena menjalani mimpi mereka?" Aku membalikkan badan, menatap bibi yang kini berdiri di ambang pintu kamar mandi. Mataku yang mulai berair membuat wujud bibi menjadi agak kabur. "Katakan padaku, Bi. Apakah seorang anak sanggup menjalani hidupnya ketika ia tak punya siapa-siapa lagi kecuali seorang bibi yang bahkan tak menanyakan keadaan keponakannya setelah orang tua anak itu dikabarkan meninggal?"
"Auleen ..." Bibi memanggil lemah, namun terlalu pelan untuk menghentikan ocehanku.
"Jawab, Bi! Apa seseorang yang pincang mampu berjalan baik tanpa penopangnya?" Kugertakkan gigi, sementara bibi menunduk dalam-dalam. "Karena kalau aku tak akan sanggup untuk menjalani semua ini."
Setelah itu tangisku pecah, kemudian berlari keluar tangga dengan langkah berderap. Aku tidak yakin bagaimana perasaan bibi bila kutinggal begitu saja. Namun, satu hal yang pasti. Mungkin ini terakhir kali ia melihatku sebab aku akan kembali bersatu dengan abuku. []
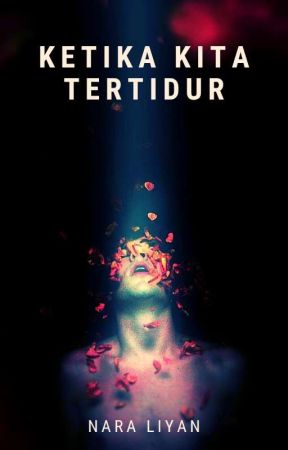
KAMU SEDANG MEMBACA
Ketika Kita Tidur
Short Story[15+] Ketika kita tidur, banyak hal yang tak kauketahui terjadi. Tetesan air dari keran wastafel, dentingan sendok di dapur, atau televisi yang tiba-tiba menyala sendiri. Di lain waktu ada ketukan di jendela kamarmu dan suara pintu depan yang terbuk...
