"Maira!" Pak Imran berteriak di depan pintu kamar Maira, tapi tidak kunjung ada sahutan dari dalam sana.
"Nak, Ayah masuk ya?"
Klek
Tanpa menunggu jawaban, perlahan Pak Imran memutar kenop pintu yang tidak terkunci itu, lalu masuk ke dalam. Maira tidak ada, dan sekarang dia baru ingat kalau Maira keluar lima menit lalu, hendak ke warung membeli kopi.
Pak Imran terkekeh sambil menggeleng sendiri. "Haduh, gejala menjadi orang tua, jadi gampang lupa. Maira kan sedang ke warung." gumamnya.
Karena terlanjur sudah masuk, dia pun iseng memerhatikan dekorasi kamar berdinding merah muda itu. Terlihat di atas meja ada sebuah bingkai foto Maira saat masih kecil, sedang dipeluk oleh kedua orang tuanya, ketiganya tertawa. Lalu ada juga di dinding, foto-foto Maira bersama sang ayah, saat dia masih mengenakan seragam paud hingga putih abu-abu. Sejak kecil kecantikan Maira sudah terpancar jelas, makin bertambah usia makin bertambah kecantikannya. Pak Imran tersenyum haru melihat semua foto itu, dia tidak pernah menyangka bisa merawat anaknya seorang diri hingga sudah sebesar sekarang.
Rasanya baru kemarin Maira digendong olehnya, dan sekarang anaknya sudah menjadi gadis saja. Sungguh, membesarkan anak perempuan seorang diri bukanlah hal mudah. Setiap hari Pak Imran selalu dihantui rasa takut, takut jika anak semata wayangnya itu dirusak. Namun dia percaya, Maira adalah anak yang baik. Maira selalu patuh pada perintahnya. Bahkan hingga kini, belum pernah ada satu teman lelaki pun yang datang ke rumah, dan Pak Imran sangat bangga akan hal itu.
Pak Imran menarik laci, berniat ingin mengecek buku tugas anaknya, takut jika Maira belum mengerjakan PR.
Namun, apa yang dia lihat di dalam laci justru bukan hanya buku-buku tugas, melainkan ada sekotak susu dan berbagai vitamin ibu hamil. Pak Imran menggeleng, berusaha menepis pikiran buruknya.
Naas, perasaannya malah kian hancur ketika menemukan selembar kertas yang terlipat di bagian laci paling bawah.
"Tidak mungkin." tangannya bergetar hebat ketika membaca lembaran kertas dari rumah sakit itu, yang menerangkan dengan jelas jika anaknya yang bernama Humaira memang sedang hamil.
"Ayah!" kresek di tangan Maira jatuh begitu saja, Maira membeku di ambang pintu dengan wajah gelisah.
Sudah waktunya sang ayah tahu hal ini, entah apa yang akan terjadi pada hidup Maira selanjutnya, Maira pasrah. Hanya satu saja keinginannya, dia tidak ingin dibenci oleh ayahnya.
"Ayah ...." Maira terisak, meski takut dia tetap mendekati ayahnya.
Pak Imran menatapnya dengan mata memerah. "Apa ini? Apa ini Humaira?!" tanyanya berang kemudian mencampakkan kertas itu ke lantai.
Maira tersentak sambil memejamkan matanya erat. Demi Tuhan, belum pernah dia mendengar suara bentakan sang ayah. Ini kali pertama Pak Imran membentaknya, dan langsung menusuk ke hati.
"Maaf Ayah ...." Maira menunduk, air matanya sudah mengalir deras.
Pak Imran mendekat, tubuh Maira digoncang-goncang dengan kasar. Maira sudah menggigil ketakutan.
"Siapa? Siapa lelaki itu?!!"
"Oh, gitu? Gimana kalo hidup ayah lo juga bakal hancur? Masih gak takut? Gue bisa aja bikin dia mati hari ini—"
Maira menggeleng lemah ketika ucapan Anfal kembali terngiang di telinganya. Dia bersumpah, bahkan meski ayahnya akan membunuhnya sekalipun, dia tidak akan pernah mengatakan siapa ayah dari bayi yang sedang dikandungnya. Maira tidak ingin pertanggungjawaban dari Anfal, Maira sudah sangat kecewa dan benci pada lelaki itu. Anfal tidak mengharapkan bayi ini, jadi untuk apa Maira mengharapkan pertanggungjawabannya? Dia bisa, dia bisa menjaga dan merawat anaknya sepenuh hati, meski hanya seorang diri. Maira yakin akan hal itu.
"Jawab Humaira!!!"
"Maaf Ayah ...." hanya kata itu yang bisa Maira ucapkan sejak tadi.
Pak Imran menangis, benar-benar remuk hatinya mengetahui semua ini. Apa yang sangat dia takutkan telah terjadi. Dia sudah gagal menjadi ayah. Ini perasaan sesak yang amat menyakitkan.
Marah, kesal, sakit semuanya berpadu dalam hati. Namun, dia tidak bisa menyakiti Maira. Sebesar apapun kesalahan Maira, Maira masih anaknya dan akan selalu begitu. Sejak anak itu hadir dalam hidupnya, dia sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah menyakitinya. Karena jika dia menyakiti Maira, itu sama saja dengan dia menyakiti diri sendiri.
"Tolong Maira, jawab Ayah ... siapa lelaki yang sudah menghamili kamu?" kali ini Pak Imran bertanya dengan suara pelan dan agak bergetar, berharap anaknya mau berterus terang.
Maaf Ayah, Maira gak bisa bilang sama ayah.
Maira kembali menggeleng. "Ayah, tolong jangan benci Maira ... maafin Maira ya?" Maira meraih tangan ayahnya penuh permohonan.
Pak Imran menepis tangannya kasar. Jika mengikuti bisikan iblis, mungkin sudah dia tampar wajah Maira. Namun dia tahu, hal itu tidak akan ada gunanya selain meninggalkan rasa sesal.
"Kamu sudah mengecewakan Ayah."
Hancur. Itu ucapan paling menyakitkan yang pernah Maira dengar dari mulut ayahnya. Tangis Maira kian lirih, Ayahnya sudah sangat kecewa, tidak ada lagi yang bisa diharapkan.
Susah payah Pak Imran menjaga anaknya, membesarkannya dengan penuh cinta. Inikah balasan yang dia dapat dari anaknya?
Maira, apa yang sudah kamu lakukan, Nak? Bukankah sejak kecil ibu dan ayah sudah mengajarimu ilmu agama? Lupa kah kamu dengan semua itu? Lupa kamu jika ada Allah yang Maha Mengetahui? Ayah malu, Nak. Ayah malu pada Tuhan.
Bugh!
Tidak ada pelampiasan amarah terbaik saat ini selain tembok. Pak Imran menghantam tembok di depannya dengan kasar hingga tangannya terluka. Rasa perih sama sekali tidak dihiraukan, malah dia merasa belum puas dan ingin menonjok tembok itu terus-menerus bahkan hingga tangannya patah sekalipun, asal amarahnya yang sudah meletup-letup itu bisa diledakkan.
"Ayah!" Maira memekik panik melihat tangan ayahnya yang sudah berlumuran darah.
Ketika Maira hendak meraih tangannya, dengan kasar Pak Imran kembali menepis. Kedua tangannya terkepal kuat, napasnya naik-turun tidak beraturan, urat di lehernya terlihat jelas. Maira meneguk air liur susah payah. Dia takut melihat sosok hangat yang kini menjadi amat dingin itu.
"Saya malu pada Tuhan."
Maira membeku, menatap ayahnya tidak percaya. Saya? Pak Imran bahkan enggan menyebut nama 'ayah' lagi. Tidak... Maira tidak sanggup menerima kenyataan ini.
Maira bertekuk lutut, memeluk kedua kaki ayahnya. Dia siap untuk bersujud di depan ayahnya sekarang juga jika beliau meminta.
"Ayah ... Ayah udah janji gak akan benci sama Maira, sebesar apapun kesalahan Maira sama Ayah—"
"Bukan pada saya, tapi pada Tuhan! Minta maaflah pada Tuhan!" bentak Pak Imran murka, lalu berusaha melepaskan kakinya.
Maira terisak pilu, kepalanya ditundukkan. Dia menggeleng lemah. "Jangan benci Maira Ayah, maaf ...." rintihnya.
Brak!
Pintu kamar ditutup kasar. Maira tersentak, sakit di hatinya kini amat sulit dijelaskan, ini titik terkelam dalam hidupnya. Malam ini Maira mengenal sosok baru ayahnya, dan dia sangsi bahwa ayahnya akan terus bersikap seperti ini, entah akan sampai kapan. Satu hal yang juga Maira sadari, bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan perlakuan hangat darinya lagi.
Perlahan Maira mengusap lembut perutnya, dia masih bisa tersenyum di tengah isakannya.
Nak, Mama gak pernah punya pikiran untuk melenyapkan kamu barang satu detik pun. Kamu tidak bersalah, kamu layak untuk hidup.
Meski apapun yang terjadi di kemudian hari, Maira sudah berjanji untuk selalu menjaga buah hatinya. Meski terjalnya jalan yang akan dia tempuh, dia berjanji untuk selalu kuat. Maira sudah menyayanginya, dia sumber kekuatan baru untuk Maira.
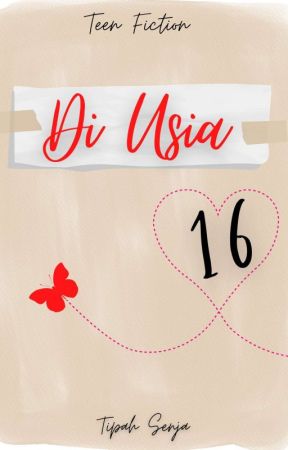
KAMU SEDANG MEMBACA
Di Usia 16(Terbit)
Fiksi Remaja(Novel Di Usia 16 sudah tersedia di toko buku offline dan online @maple_books) Maira masih menunduk, tidak berani menatap lawan bicaranya saat ini, sebab sejak tadi cowok itu hanya memasang wajah datar. Kedua tangannya sibuk mencengkeram rok sekolah...
