Sudah satu jam berlalu sejak Maira izin masuk ke kamar, dan hingga kini dia tidak ada keluar lagi. Muak rasanya mendengar ucapan Tante Hanum yang begitu pedas. Maira sadar jika dirinya memang bersalah, tapi apa harus tantenya sendiri bicara begitu padanya?
Dia boleh menghina Maira. Semua orang boleh menghina Maira, tapi Maira tidak akan pernah terima jika ada orang yang menghina anaknya. Sekecil apapun jenis penghinaan itu, Maira tidak akan bisa menerima. Ini buah hati Maira, siapa mereka berhak menilai anaknya?
"Kamu anak baik, anak hebat, anak Mama," bisik Maira berkali-kali sambil mengusap perutnya dengan lembut.
Sementara itu di ruang tengah, wajah Pak Imran terlihat serius berbincang dengan Tante Hanum dan suaminya.
"Baik. Hanum akan merawat Maira sampai dia melahirkan," putus Tante Hanum.
Maira membeku di balik pintu, niatnya untuk ke sana kembali diurungkan. Dia tidak percaya, jika ayahnya menginginkan dia untuk pergi dari rumah ini.
"Tapi dengan satu syarat," lanjut Tante Hanum.
Pak Imran yang semula bisa membuang napas lega langsung kembali menatap adiknya penuh tanya.
"Apa?"
"Setelah lahir, anak itu harus diberikan ke panti asuhan."
Sekujur tubuh Maira melemas, aliran darahnya seperti berhenti mengalir selama beberapa detik. Dia menggeleng, ingin keluar untuk membantah permintaan itu, tapi takut semakin memperkeruh keadaan.
"Apa tidak ada jalan lain?" Pak Imran tampak keberatan.
Meski bagaimanapun, meski siapapun ayah dari bayi itu, tapi tetap saja dia cucunya. Ada perasaan tidak rela ketika mendengar bayi yang bahkan belum lahir itu akan diberikan ke panti asuhan. Tinggal di panti bukanlah harapan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua, itu pasti akan sangat menyiksa.
Tante Hanum menggeleng. "Sekarang Mas pikirkan, gaji Mas Indra itu pas-pasan. Hanum masih menumpang di rumah mertua, belum lagi ada dua anak yang masih kecil-kecil. Kalau ditambah Maira, bertambah pula bebannya—"
"Mas janji akan kirim uang setiap bulan." potong Pak Imran.
"Bukan hanya itu masalahnya. Lihat, perut Maira sudah besar, beberapa bulan lagi dia akan melahirkan. Biaya bersalin, membeli peralatan bayi, belum lagi susu jika ASI Maira tidak ada. Itu akan menghabiskan uang yang tidak sedikit. Jika anak itu dirawat di rumah kami, kami angkat tangan, Mas."
"Maaf, Mas. Kami sama sekali tidak keberatan jika Maira tinggal di Malang, tapi untuk anak itu ... kami rasa memang terlalu berat jika harus dirawat juga." ujar Mas Indra, suami Tante Hanum.
Selanjutnya Maira tidak bisa lagi fokus mendengarkan perkataan mereka, karena dia sudah berjalan menuju lemari, lalu memasukkan baju-bajunya ke dalam tas besar.
Di tengah pikirannya yang kacau, Maira berniat ingin pergi dari rumah. Ya, Maira harus pergi dari sini. Dia sudah menjadi beban banyak orang. Dia tidak mau tinggal bersama Tante Hanum, dia tidak rela, sampai matipun dia tidak akan rela jika anaknya diberikan ke panti asuhan.
23:22
Maira membuka pintu kamar dengan begitu pelan hingga tidak menimbulkan suara sedikitpun. Dia melihat ruang tengah yang hanya terdengar suara dengkuran dengan lampu yang dimatikan, di tengah remang-remang itu dia masih bisa melihat sosok ayahnya dan suami Tante Hanum sedang tidur pulas beralaskan tikar, sementara Tante Hanum pasti tidur di kamar ayahnya.
Sambil menenteng tas besar yang lumayan berat di tangan, Maira berjalan dengan langkah sangat hati-hati menuju pintu keluar. Ketika sampai di ambang pintu utama, dia menatap wajah ayahnya lama, takut jika tidak akan melihatnya lagi.
Maira yakin ini keputusan terbaik. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di luar sana, dia sudah pasrah. Keinginan Maira sederhana, hanya tidak ingin dipisahkan dengan anaknya. Dan Maira jelas tidak akan mau menuruti keinginan Tantenya. Dia lebih rela mati daripada harus dipisahkan dengan anaknya kelak.
Maafin Maira Ayah kalau selama ini sudah mengecewakan Ayah, Maira sayang Ayah.
Maira membuka pintu perlahan, lalu melangkah keluar. Setelah berada di luar, segera dia menutup pintu itu kembali. Dia tidak yakin, apakah dia bisa pulang ke rumah ini lagi? Jujur, dia tidak mau berpisah dari ayahnya, tapi sekali lagi dia harus percaya jika ini adalah keputusan terbaik.
Tujuan utama Maira setelah meninggalkan rumah adalah terminal. Dia harus segera pergi ke sana.
Bandung, itulah kota tujuannya saat ini. Dia tidak tahu kenapa dari sekian banyaknya bus yang terparkir di terminal, harus arah Bandung yang dia tuju. Entah karena jaraknya yang tidak begitu jauh, atau karena menurutnya orang Bandung itu ramah-tamah. Entahlah, Maira sudah tidak bisa berpikir jernih.
Dia menyandarkan kepalanya pada senderan kursi, jaketnya dirapatkan demi menahan udara dingin yang menusuk di tengah malam. Pandangannya kosong, sama seperti hatinya.
Maira tidak pernah berpikir jika jalan hidupnya akan se-menyedihkan ini hanya karena kesalahan di satu malam. Sekarang dia harus berlindung pada siapa? Ayah yang selama ini menjadi pamong baginya telah dia tinggalkan. Dia benar-benar kacau.
Dia sudah mengecewakan ayahnya, dia sudah menyakiti hatinya, dia gagal menjadi anak yang baik. Ibunya di sana pasti sudah sangat kecewa dan menyesal telah melahirkan anak tidak berguna seperti dia.
Maira adalah anak tunggal, harapan satu-satunya. Sejak kecil dia sudah tahu jika hidupnya susah dan selalu dipandang rendah. Harusnya hal itu bisa memotivasi dirinya agar berkembang dan berpikiran maju untuk menjadi seseorang yang berguna, yang bisa membahagiakan orang tuanya. Namun apa yang dia lakukan? Dengan mudahnya dia berhasil dibodohkan oleh cinta hingga lupa pada tujuan hidupnya di masa depan. Dia telah menghancurkan segalanya.
Dia malu pada Tuhan, dia malu pada ayahnya, dia malu pada semua orang. Apa jika dirinya mati semua akan menjadi lebih baik?
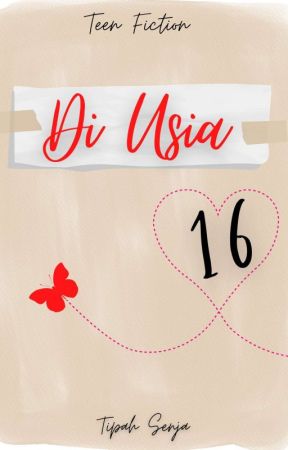
KAMU SEDANG MEMBACA
Di Usia 16(Terbit)
Fiksi Remaja(Novel Di Usia 16 sudah tersedia di toko buku offline dan online @maple_books) Maira masih menunduk, tidak berani menatap lawan bicaranya saat ini, sebab sejak tadi cowok itu hanya memasang wajah datar. Kedua tangannya sibuk mencengkeram rok sekolah...
